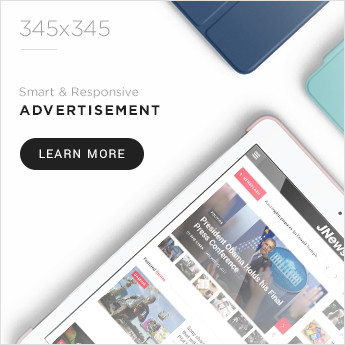Puasa Berulang, Makna Hilang
Catatan Kecil Menyambut Ramadhan
oleh: A. U. Chaidir
Sebentar lagi kita akan kembali memasuki bulan Ramadhan. Bulan yang selalu datang dengan suasana religius: masjid lebih ramai, lantunan ayat terdengar di mana-mana, dan kata puasa kembali menjadi tema utama kehidupan umat Islam.
Namun, ada satu kegelisahan yang pelan-pelan tumbuh di dalam diri penulis—dan mungkin juga di dalam diri sebagian dari kita: mengapa puasa yang telah kita jalani bertahun-tahun sering kali tidak menghadirkan perubahan yang berarti dalam hidup dan masyarakat kita?
Penulis tidak sedang menuduh siapa pun. Termasuk diri penulis sendiri. Penulis pun sadar bahwa penulis masih dalam perjalanan dan masih mencari.
Puasa yang Dilakukan, Tapi Tidak Dihidupi
Tidak sedikit dari kita yang telah berpuasa puluhan kali Ramadhan. Secara lahiriah, puasa itu sah: menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkannya. Namun secara batin, kita jujur harus bertanya: apa yang sesungguhnya berubah dalam diri kita?
Al-Qur’an tidak menyebut tujuan puasa adalah pahala, meski pahala itu nyata. Yang disebut justru adalah taqwa—sebuah kesadaran batin, kewaspadaan moral, dan kejernihan hati dalam menjalani hidup.
Jika setelah bertahun-tahun berpuasa:
* amarah kita tetap liar,
* empati kita tetap tumpul,
* kejujuran kita tetap rapuh,
maka mungkin yang berulang hanyalah ritualnya, bukan transformasinya.
Puasa yang Direduksi Menjadi Kewajiban
Puasa sering dipahami sekadar sebagai:
* penggugur kewajiban tahunan,
* sarana mengumpulkan pahala,
* rutinitas religius yang “harus dijalani”.
Tanpa disadari, puasa kehilangan daya latihnya. Padahal puasa sejatinya adalah:
* latihan menundukkan ego,
* latihan kejujuran (karena hanya Allah yang tahu),
* latihan empati terhadap yang lapar dan lemah,
* latihan mengendalikan hasrat, bukan sekadar menahannya sementara.
Ketika dimensi ini tidak disadari, puasa menjadi kering—sah secara fiqh, tapi miskin makna.
Ceramah yang Menghibur, Tapi Tidak Mengubah
Kegelisahan ini ditambah oleh mimbar-mimbar Ramadhan yang hanya berkutat pada keutamaan dan pahala (tidak salah). Pahala memang penting, tapi puasa bukan sekadar soal “berapa yang kita dapat”, melainkan “siapa yang sedang kita bentuk”.
Ceramah yang terlalu aman sering kali:
* membuat kita merasa cukup,
* merasa sudah benar,
* merasa sudah saleh,
tanpa mengajak kita bertanya lebih dalam: apa yang sedang Allah latih dalam diriku melalui puasa ini?
Kerisauan Sebagai Tanda Kesadaran
Menariknya, kegelisahan ini justru bisa menjadi tanda bahwa puasa belum mati sepenuhnya dalam diri kita. Orang yang ibadahnya kosong biasanya tidak resah. Ia berjalan tanpa bertanya, tanpa gelisah, tanpa keinginan untuk berubah.
Maka kegelisahan—tentang diri sendiri dan masyarakat—bisa jadi adalah pintu awal kesadaran.
Menyambut Ramadhan dengan Kejujuran
Tulisan ini tidak menawarkan resep instan. Juga tidak mengklaim jalan paling benar. Ia hanya mengajak kita menyambut Ramadhan dengan satu sikap sederhana tapi mendasar: kejujuran batin.
Bahwa kita masih belajar.
Bahwa kita masih sering gagal.
Bahwa puasa bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab dalam hidup.
Mungkin Ramadhan kali ini tidak harus dimulai dengan target besar. Cukup dengan satu niat kecil namun jujur:
“Ya Allah, jangan biarkan puasaku hanya menahan lapar,
tapi jadikan ia jalan untuk membentuk hatiku.”
Pekanbaru, 5 Februari 2026