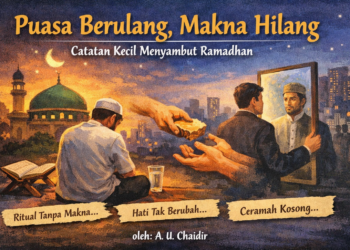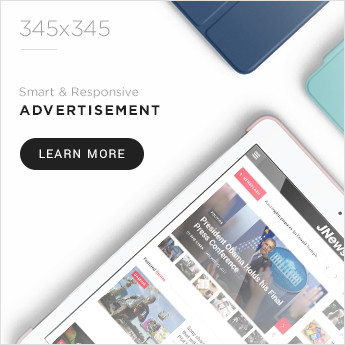Ketika Arah Pendidikan Terasa Bergeser
Kegelisahan atas Realitas Pendidikan vs Cita-cita Ki Hadjar Dewantara
Oleh: A. U. Chaidir
Ada kegelisahan yang belakangan ini sulit penulis abaikan. Ia tidak lahir dari satu peristiwa besar, melainkan dari pengamatan sehari-hari tentang bagaimana pendidikan dipahami dan dijalankan di tengah masyarakat kita dewasa ini. Pendidikan, yang sejatinya merupakan proses memanusiakan manusia, perlahan direduksi menjadi alat mobilitas sosial. Di tingkat keluarga, khususnya orang tua, pendidikan sering dimaknai melalui jalur yang dianggap paling aman: memilihkan sekolah yang baik agar anak kelak memperoleh pekerjaan yang baik. Niat ini tentu tidak keliru. Namun persoalan muncul ketika anak tidak lagi diperlakukan sebagai subjek yang memiliki potensi dan kecenderungan unik, melainkan sebagai objek yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Program studi dipilih berdasarkan tren dan peluang ekonomi, bukan minat dan bakat. Target pendidikan menyempit pada ijazah dan transkrip nilai, sementara pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual justru terpinggirkan. Padahal, sejak awal kemerdekaan pemikiran pendidikan bangsa ini telah diletakkan di atas landasan yang jauh lebih manusiawi.
Ki Hadjar Dewantara merumuskan tujuan pendidikan sebagai upaya “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”
Kata menuntun menjadi kunci. Pendidikan, menurut Ki Hadjar, bukanlah proses membentuk apalagi memaksa, melainkan mendampingi pertumbuhan potensi anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam pandangan ini, pendidik dan orang tua bukan pencetak manusia, tetapi penuntun arah.
Sayangnya, makna luhur ini kian menjauh dari praktik. Di tingkat masyarakat, pendidikan tinggi dan gelar akademik menjelma simbol status sosial. Ilmu tidak lagi dimuliakan karena kedalaman pemahaman dan kebijaksanaannya, melainkan karena prestise yang melekat padanya. Menuntut ilmu pun kerap berorientasi pada akumulasi materi, bukan pada pengabdian dan pencarian makna hidup.
Akibatnya, pendidikan melahirkan paradoks: semakin banyak orang berpendidikan tinggi, namun semakin terasa krisis keteladanan, empati, dan tanggung jawab sosial.
Gelar akademik sering dijadikan syarat administratif untuk menduduki posisi tertentu, seolah-olah ia otomatis menjamin kapasitas dan integritas. Padahal, Ki Hadjar justru menempatkan manusia merdeka—manusia yang berpikir mandiri, berkarakter, dan bertanggung jawab—sebagai tujuan akhir pendidikan.
Yang lebih mengkhawatirkan, dunia pendidikan sendiri tidak sepenuhnya berdiri sebagai penyeimbang arus ini. Dalam situasi tertentu, pendidikan diposisikan sebagai komoditas, kampus sebagai industri, dan peserta didik sebagai konsumen. Logika pasar perlahan menggantikan nilai-nilai pedagogis.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, pertanyaan mendasar patut kita ajukan: manusia seperti apa yang sedang kita bentuk melalui pendidikan? Apakah negeri ini sedang menyiapkan generasi yang utuh—cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat secara moral—atau sekadar tenaga kerja terampil yang rapuh secara batin?
Tulisan ini bukan tudingan, apalagi penghakiman. Ia hanyalah kegelisahan seorang warga yang percaya bahwa pendidikan seharusnya mengantarkan manusia pada keselamatan dan kebahagiaan, bukan sekadar pada pekerjaan dan status sosial.
Mungkin sudah waktunya kita kembali menengok cita-cita pendidikan yang pernah dirumuskan dengan jernih oleh para pendiri negeri ini, dan bertanya dengan jujur:
sejauh mana pendidikan kita hari ini masih setia pada tujuan itu?
Pekanbaru, 11 Februari 2026